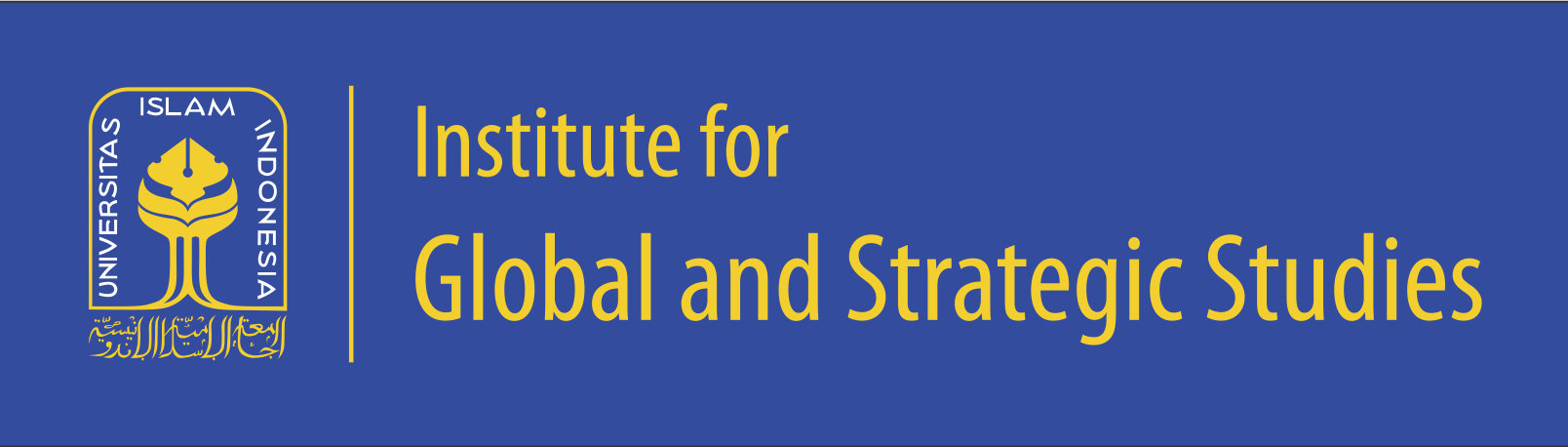Dalam fikih prioritas, meninggalkan sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya adalah pilihan terbaik (Qardhawi, 2006). Salah satu implementasinya adalah meninggalkan gagasan pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi (PT). Gagasan untuk menyejahterakan PT melalui pemberian izin pengelolaan tambang, baik secara langsung maupun lewat BUMN, berpotensi bertabrakan dengan banyak norma. Benturan dengan norma-norma ini akan berdampak signifikan dalam meluruhkan martabat PT. Tulisan ini bertujuan menambah argumen negasi yang sudah ada, namun dari sudut pandang norma internasional.
Norma Keadilan
Sampai saat ini, usulan pemberian izin pengelolaan tambang pada PT masih abstrak, namun dampak buruknya telah dapat diterawang. Pertama, pengelolaan yang dilakukan oleh PT berpotensi bertabrakan dengan norma keadilan. Paling tidak, pengelolaan tambang oleh PT akan bermasalah dengan keadilan distributif. Norma keadilan distributif mensyaratkan pembagian yang wajar atas sumber daya yang ada, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak. Pembagian izin pengelolaan tambang pada PT akan runyam mengingat jumlah PT yang mencapai lebih dari 5000 institusi, jenis yang beragam, kekuatan finansial yang berbeda, kemampuan manajerial yang tidak sama, jumlah mahasiswa yang tidak merata, dan lokasinya yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Akan sulit untuk membayangkan, agar adil, kira-kira pembagian izin tambang tersebut didasarkan atas apa? Atas dasar jenis PT atau atas kemampuan manajerial berdasarkan akreditasi dan peringkat? Jika menggunakan kedua kriteria ini saja, maka hanya PT yang berada di Pulau Jawa sajalah yang akan mendapat izin tambang. Padahal lokasi industri pertambangan kebanyakan di luar Pulau Jawa. Lalu bagaimana dengan PT yang dekat dengan industri tambang? Berkolaborasi dengan PT di Jawa? Pembagian kerja dan hasilnya bagaimana? Bayangkan lagi bagaimana runyamnya jika izin tambang diberikan ke lebih dari 5000 PT tersebut. Alih-alih berkontribusi pada kesejahteraan PT, yang akan terjadi adalah keributan massal atas ketidakadilan pembagian jatah pengelolaan tambang.
Jika ini terjadi, maka energi PT akan terkonsentrasi pada gulat pengelolaan tambang. Energi PT yang harusnya fokus pada dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat akan tergeser pada bisnis ekstraktif yang rawan ketidakadilan. PT tidak akan lagi hadir dalam membela keadilan masyarakat, tapi justru akan membela kepentingan korporasi. Dalam hal ini, tidak ada skenario yang mendukung pencapaian keadilan baik bagi masyarakat maupun antar-PT jika PT mengelola tambang.
Norma Transparansi Industri Ekstraktif
Kedua, pengelolaan tambang oleh PT akan berpotensi menjebak PT dalam pelanggaran norma transparansi industri ekstraktif. Norma transparansi industri ekstraktif ini dilembagakan dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) yang berdiri sejak 2003 (EITI, n.d.). Setiap tahunnya, 52 negara yang berkomitmen pada norma transparansi industri ekstraktif mengirimkan laporan ke EITI. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dan menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang telah mengirimkan laporannya sejak tahun 2007 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Dalam validasi EITI atas laporan Indonesia pada tahun 2024, skor keseluruhan Indonesia adalah 63/100 atau terkategori “fairly low.” Meskipun Indonesia telah berkomitmen melaporkan informasi terkait industri ekstraktifnya, masih terdapat celah dalam pelaporan tersebut. EITI mencatat adanya masalah data yang tidak dipublikasi dan data yang belum dapat diverifikasi kesesuaiannya. Data yang tidak dipublikasi di antaranya adalah data kontrak bisnis dan nilai produksi, sedangkan yang belum terverifikasi adalah data beneficial ownership atau pemilik manfaat akhir dari usaha tambang tersebut.
Lebih jauh lagi, laporan independen dari Transparency International Indonesia (TII) tahun 2024 memberikan skor 0,31 atau sangat rendah pada aspek transparansi korporasi untuk aspek antikorupsi. Sedangkan skor 0,30 yang juga setara dengan sangat rendah untuk transparansi aspek sosial dan hak asasi manusia (HAM). TII juga menemukan bahwa hanya 17 dari 121 perusahaan tambang yang mempublikasikan laporannya di laman perusahaan. Rendahnya komitmen perusahaan tambang dalam upaya antikorupsi menunjukkan bahwa industri tambang merupakan industri yang sangat rawan korupsi. Lingkup korupsi ini bisa dimulai dari proses perizinan sampai pengawasan kegiatan pertambangan. Longgarnya regulasi dan orientasi maksimalisasi keuntungan juga berkontribusi terhadap tingginya risiko korupsi dan kerusakan lingkungan.
Jika PT diberikan izin pengelolaan tambang, tidak ada jaminan pelaporannya akan lebih transparan. Yang ada, PT akan terseret dalam pusaran kasus korupsi tambang. Berkaca pada kasus Harvey Moeis, kasus pidana korupsi tambang melibatkan kerugian negara sampai ratusan triliun rupiah. Berat rasanya membayangkan seorang insan cendekia kampus atau guru besar didakwa kasus korupsi tambang dengan kerugian negara yang sebegitu besar. Jika ini benar-benar terjadi, maka lunturlah kepercayaan masyarakat terhadap PT yang menjadi suar etika dan moral bangsa.
Norma Perlindungan HAM
Ketiga, PT juga berisiko terlibat dalam pelanggaran norma perlindungan HAM. Pelanggaran HAM akibat dari usaha pertambangan bukan omong kosong. Komisi Nasional (Komnas) HAM menyampaikan laporan pelanggaran HAM atas usaha pertambangan di berbagai daerah. Dalam laporannya tahun 2022, Komnas HAM mencatat pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah berupa penyerobotan tanah, penembakan oleh oknum polisi pada aksi demo menolak tambang, dan penutupan akses bagi warga dalam pemanfaatan ruang untuk pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat Poboya. Pada tahun yang sama, Amnesty International juga menyoroti pelanggaran HAM atas rencana penambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua (Amnesty International, 2022). Rencana penambangan ini akan melanggar hak-hak warga adat dan berpotensi merusak lingkungan sekitarnya.
Sekali lagi, mari kita bayangkan jika PT diberikan izin mengelola tambang di daerah seperti Intan Jaya. Tidak ada jaminan bahwa PT akan lebih diterima oleh masyarakat adat. Yang pasti, PT akan terlibat dalam pelanggaran HAM masyarakat adat, menghilangkan sumber makanan utama mereka, mencemari lingkungan, dan memaksakan kepentingan dengan kekerasan. Tidak ada hal hebat yang akan didapat oleh PT atas pelanggaran HAM tersebut. Yang ada, PT Indonesia akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan di dunia yang melakukan pelanggaran HAM atas dasar kesejahteraan PT.
Pelanggaran atas tiga norma ini saja rasanya cukup untuk menangkis argumen pemerintah dan selintir PT yang mendukung gagasan pengelolaan tambang oleh PT. Para cerdik pandai di PT tahu betul bahwa kesesatan dalam berpikir akan melahirkan kerusakan dunia yang nyata. Semoga tidak terjadi.
Referensi
Qardhawi, Yusuf. (2006). Fi Fiqhil Aulawiyyat. Kairo: Maktabah Wahbah
EITI. (n.d.). https://eiti.org/our-mission. Diakses pada 1 March 2025.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Laporan EITI Indonesia 2019-https://portaldataekstraktif.id/storage/post-
file/20240604163711/laporan%20eiti%20indonesia%202019-2020.pdf. Diakses
pada 1 Maret 2025.
Amnesti Internasional. (2022). Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu
Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/03/Perburuan-Emas.pdf. Diakses pada 1 Maret 2025