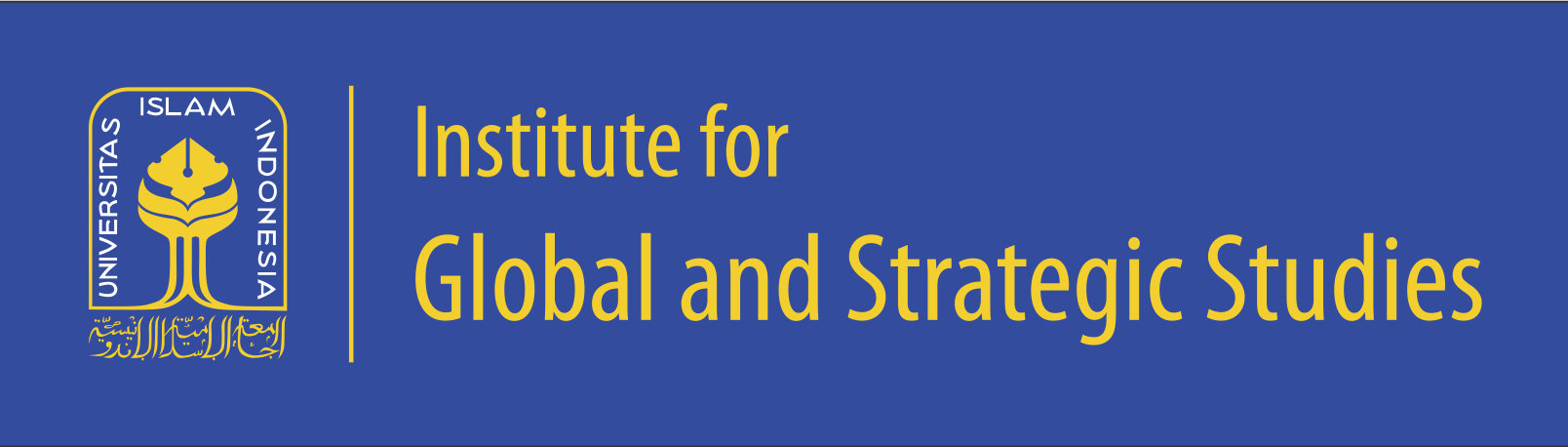Beberapa pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua pidato terpisah dalam dua forum yang berbeda saat berlangsungnya HLW (High Level Week) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Pidato pertama Prabowo disampaikan di Konferensi Tingkat Tinggi Penerapan Solusi Dua Negara, dimana dalam pidato tersebut Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan segera mengakui Israel dengan kondisi bahwa Israel mengakui eksistensi Palestina. Dalam pidato keduanya, Prabowo juga menyampaikan bahwa seiring dengan pengakuan terhadap Palestina oleh Israel, Indonesia juga akan menjamin keamanan Israel.
Pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini memicu kontroversi yang tak berkesudahan di media sosial. Adanya afirmasi positif Netanyahu terhadap pidato Prabowo makin memperuncing perdebatan ini.
Masyarakat terbelah menjadi dua, dimana ada pihak yang mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai solusi yang paling realistis dan paling adil di antara semua solusi yang ada.
Pihak lain berdiri pada solusi satu negara (one-state solution), sebagai sebuah solusi yang dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan kemanusiaan oleh entitas Israel dan memastikan bahwa tidak ada negara yang diberikan lisensi lagi untuk melanjutkan penjajahan di tanah Palestina.
Di tengah perdebatan ini, solusi satu negara dianggap sebagai tabu dan impian di siang bolong.
Kontroversi ini penting untuk dibahas secara lebih mendalam, karena pengakuan terhadap eksistensi entitas yang disebut Israel di tengah genosida yang tiap hari menimbulkan korban di Gaza perlu dipertimbangkan secara serius.
Pemberian pengakuan terhadap entitas Israel yang sedang melakukan genosida justru akan melanggengkan impunitas dan mencegah keadilan untuk dapat ditegakkan secara penuh.
Hal pertama yang perlu kita sama-sama gugat adalah: mengapa solusi dua negara seolah menjadi hegemonik dan dianggap paling realistis, sedangkan solusi satu negara menjadi tabu yang tak layak dibicarakan?
Simalakama Solusi Dua Negara
Wacana solusi dua negara menjadi wacana yang hegemonik karena wacana ini terbentuk melalui proses perdamaian antara Israel, Palestina dan negara-negara di kawasan Arab yang dikawal sejak tahun 1967 oleh Amerika Serikat.
Pendekatan solusi dua negara berkembang dari formulasi “land for peace” atau pengembalian/pertukaran teritori oleh pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan damai (Rynhold, 2001). Pendekatan ini awalnya untuk menggunakan untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dan Mesir di Semenanjung Sinai. Adanya mekanisme tersebut kemudian dipakai sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa yang berjung pada rentetan negosiasi antara pihak Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization atau disebut juga PLO) (Hallward, 2011).
Perjanjian Oslo I & II yang disepakati oleh Israel dan PLO berangkat atas basis land for peace, dimana kedua belah pihak menyepakati pembagian lahan untuk memastikan perdamaian dapat berlangsung secara berkelanjutan antara pihak Israel dan Palestina.
Bagi kalangan politisi progresif di Israel, land for peace merupakan kunci dari terbangunnya relasi organik antar masyarakat Israel dan Palestina. Interaksi tersebut dibangun melalui kawasan ekonomi bersama seperti di kawasan Barkan, Tepi Barat, dimana kolaborasi ekonomi antara masyarakat Israel dan Palestina diharapkan membangun saling percaya dan persepsi positif antar kedua bangsa (Qumsieh, 1998).
Namun, tentu saja, kerangka solusi dua negara dalam kerangka Perjanjian Oslo memiliki simalakama yang memunculkan lebih banyak petaka bagi warga Palestina.
Petaka pertama adalah manipulasi Israel terhadap Perjanjian Oslo yang memungkinkan pendirian banyaknya pemukiman ilegal di kawasan Tepi Barat. Riset Gordon & Cohen (2012) menyebutkan bahwa semua partai di Israel, terlepas dari ideologinya, membuka kesempatan perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Perluasan ini juga dimungkinkan oleh sikap Amerika Serikat dan negara-negara di Barat yang menolak untuk memberikan pengakuan terhadap Palestina.
Petaka kedua adalah kebijakan perbatasan Israel yang diberlakukan dalam kerangka penerapan Perjanjian Oslo bersifat amat militeristik dan seringkali mengambat warga negara Palestina untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Laporan Amnesty International yang mengutip penelitian dan pantauan lapangan B’Tselem di tahun 2022 jelas menegaskan bahwa kehadiran pos militer di perbatasan kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza selama bertahun-tahun telah melanggar hak asasi warga Palestina untuk melanjutkan hidup dengan selayaknya (Amnesty International, 2022).
Manipulasi dan militerisasi makin diperparah di bawah rezim Netanyahu yang ultra-nasionalis. Rezim Netanyahu berkeinginan untuk meniadakan entitas negara Palestina, membuat pemberlakuan solusi dua negara menjadi jauh panggang dari api.
Urgensi Solusi Satu Negara
Adanya genosida Gaza mulai merontokkan basis ideologi Zionisme pada jantungnya, yakni masyarakat Yahudi di Israel. Ada beberapa lingkar orang-orang Yahudi yang berpikir ulang relevansi eksistensi Israel dan ideologi Zionisme.
Beberapa intelektual dan politisi Yahudi mulai menjadi pembela ulung anti-Zionisme, anti-Israel dan mendukung narasi solusi satu negara yang demokratik dan menjamin hak asasi manusia untuk semua. Salah satu intelektual Yahudi tersebut adalah Avraham Burg, mantan Ketua Parlemen Israel. Burg mendorong adanya pemikiran negara baru yang memajukan demokrasi tanpa batas etnis dan agama untuk semua pihak (Burg, 2025). Burg bahkan memulai satu langkah kontroversial untuk mencabut statusnya sebagai orang Yahudi untuk menghilangkan privilese yang ia dapatkan sebagai warga negara Israel (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, 2024).
Solusi satu negara juga dikemukakan oleh intelektual Palestina, Rashid Khalidi, yang juga beranggapan bahwa solusi terbaik bagi masalah Israel-Palestina adalah menciptakan solusi dimana dua bangsa bisa hidup dengan damai dan penuh dengan keadilan, tanpa adanya praktik settler-colonialism Israel yang menginjak hak dan martabat warga Palestina (The American University in Cairo, 2024).
Solusi satu negara bukan solusi yang tidak realistis. Beberapa riset, seperti yang dilakukan oleh Nimni (2019) membuka kemungkinan model binational state (satu negara dua bangsa) yang berdasar pada shared sovereignty (kedaulatan bersama) dan nonterritorial autonomy (otonomi tanpa basis territorial yang diklaim secara ketat) dapat diterapkan demi perdamaian dan keadilan di antara kedua bangsa.
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berjangka panjang yang akan membutuhkan proses rekonsiliasi berjalan terlebih dahulu. Selain itu, pengembalian lahan-lahan yang telah direbut paksa oleh Israel menjadi proses penting untuk mengembalikan kembali harkat dan martabat bangsa Palestina yang telah hilang sejak Nakba di tahun 1948.
Apapun yang menjadi solusi yang disepakati kedepannya, hanya bangsa Palestina yang layak memberikan jawaban akhirnya. Tentu saja, solusi ini hanya bisa diterapkan setelah para penjahat perang Israel dihukum atas segala kesalahannya.
Referensi
Amnesty International. (2022). SRAEL’S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS CRUEL SYSTEM OF DOMINATION AND CRIME AGAINST HUMANITY . Retrieved from https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/MDE1551412022ENGLISH.pdf
Burg, A. (2025, October 7). The day that never ended. Retrieved October 13, 2025, from The Observer website: https://observer.co.uk/news/international/article/october-7-the-day-that-never-ended
Gordon, N., & Cohen, Y. (2012). Western interests, Israeli unilateralism, and the two-state solution. Journal of Palestine Studies, 41(3), 6-18
Hallward, M. (2011). Pursuing” Peace” in Israel/Palestine. Journal of Third World Studies, 28(1), 185-202
Nimni, E. (2020). The twilight of the two-state solution in Israel-Palestine: Shared sovereignty and nonterritorial autonomy as the new dawn. Nationalities Papers, 48(2), 339-356
Qumsieh, V. (1998). The Environmental Impact of Jewish Settlements in the West Bank. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 5(1).
Rynhold, J. (2001). Re-conceptualizing Israeli approaches to” land for peace” and the Palestinian question since 1967. Israel Studies, 6(2), 33-52
The American University in Cairo. (2024). 10 Takeaways from Rashid Khalidi’s Talk on Palestine | The American University in Cairo. Retrieved October 13, 2025, from The American University in Cairo website: https://www.aucegypt.edu/news/10-takeaways-rashid-khalidi%E2%80%99s-talk-palestine
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. (2015). “I believe, especially after October 7th, that the area between the Jordan River and the Mediterranean, including Gaza, is ultimately one space.” Retrieved October 13, 2025, from Vidc.org website: https://www.vidc.org/en/detail/i-believe-especially-after-october-7th-that-the-area-between-the-jordan-river-and-the-mediterranean-including-gaza-is-ultimately-one-space